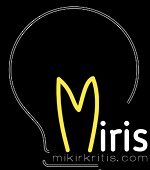Pada era 1960-an, pemerintah orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto getol merealisasikan program pengembangan daerah. Pengiriman kepala keluarga (KK) dari pulau Jawa dilakukan melalui program transmigrasi. Binuang di Kabupaten Tapin, salah satu tujuan pertama pelaksanaan program itu untuk wilayah Kalimantan Selatan.
Oleh: Rudiyanto
Tepatnya pada 1967, sekitar 400 kepala keluarga yang merupakan purnawirawan Angkatan Darat dari dua kesatuan berbeda, Komando Daerah Militer (Kodam) IV Diponegoro, Semarang, Jateng dan Kodam V Brawijaya, Surabaya, Jatim dikirim untuk babat alas atau membuka lahan Binuang yang kala itu masih perawan tak bertuan. Transmigrasi Angkatan Darat atau Transad demikian para purnawirawan itu kemudian dikenal.
Di Binuang, para purnawiraan itu menempati rumah-rumah yang telah disiapkan pemerintah. Selain mendapat rumah dan pekarangannya, para transmigran pensiunan Angkatan Darat juga mendapat jatah kavling tanah masing-masing 2 hektare untuk ladang dan perkebunan dan 1,5 hektare persawahan.
Dari sekitar 400 KK yang dikirim, Di Binuang baru terbangun 15 unit rumah berbahan papan dengan kosntruksi panggung. Alhasil, satu rumah ditempati hingga lebih dari sepuluh kepala keluarga. Sambil menggarap ladang-ladang mereka, rumah-rumah lain terus dibangun lebih permanen berbahan bata semen. Baru pada tahun 1969 semua unit rumah terbangun dan terbagi menjadi menjadi 11 blok.
Baru setelah menempati rumah masing-masing, para purnawirawan kembali ke Jawa menjemput anggota keluarganya. Sarman salah satunya. Purnawirawan Angkatan Darat, Divisi Armed 11 Magelang, Kodam IV Diponegoro ini menjemput istri dan anak tunggalnya, Dahlan Untung yang kala itu masih berumur enam tahun.
“Sampai di Binuang saya masuk SD. Karena di sekitar Binuang masih rawan dengan gerakan para gerombolan, para purnawirawan masih dipersenjatai hingga tahun 1975 demi keamanan,” kata Dahlan Untung beberapa waktu lalu.
Beberapa tahun berselang setelah kedatangan para transmigran Angkatan Darat, gelombang kedua transmigrasi, pada kisaran tahun 1970-an didatangkan dari pulau Jawa. Kali ini bukan dari kalangan purnawirawan, tapi dari kalangan masyarat umum. Kelompok ini kemudian dikenal dengan trans spontan. Para trans spontan ditempatkan berjarak sekitar 10 kilometer dari lokasi transAD, atau di sekitar ladang dan perkebunan milik para purnawirawan.
Sebagai pensiunan yang sudah berumur, keterbatasan tenaga dan pengetahuan mengolah lahan, membuat para purnawirawan menjual ladang-ladang mereka pada para transmigran spontan.
“Sebagian memang sempat digarap sendiri, tapi tak lama. Termasuk lahan milik ayah saya yang juga dijual setelah sekitar lima tahun. Pengetahuan dan pengalaman mengolah lahan, serta dana pensiunan yang diterma saban bulan alasan utama transAD menjual tanah-tanahnya,” kata Untung.
Di tangan para transmigran spontan itulah, lahan-lahan pemberian pemerintah berhasil diolah. Berbagai komoditi pertanian hasil panen warga membanjiri pasar Binuang yang kala ramai saban Rabu, hari pasaran pasar Binuang kala itu. Kacang tanah dan pisang merupakan hasil utama pertanian Binuang.
Melimpahnya hasil pertanian bumi Binuang, baik dari lokasi pertanian petani pendatang maupun masyarakat lokal yang juga menggarap ladang-ladang mereka mendorong munculnya sektor lain berupa pengolahan hasil pertanian. Khususnya hasil pertanian berupa pisang. Sebagian warga asli Binuang mengolahnya menjadi pisang sale atau dalam bahasa setempat dikenal dengan pisang rimpih.
Acil Amas , salah satu warga asli Binuang yang sejak puluhan tahun silam berprofesi sebagai pembuat pisang rimpih. Di sela-sela waktunya menggarap beberapa hectare lahan miliknya, yang juga banyak ditanami pisang, Acil Amas mengolah ratusan tandan berisi ribuan pisang di rumahnya, di Desa Sarang Burung, Binuang.
Kala pisang masih melimpah, Wanita berusia 60 tahun ini mengaku tak pernah kehabisan stok pisang awak, jenis pisang bahan baku utama pisang rimpi. Selain dari hasil panen kebunnya sendiri, Acil Amas juga membeli pisang-pisang dari tangan para petani, khususnya petani pendatang di sekitar pegunungan meratus yang kala itu masih begitu subur dan hijau.
Produksi pisang rimpih semakin meningkat saban bulan Syawal. Pisang rimpih buatannya banyak diburu orang sebagai sajian merayakan Idul Fitri atau buah tangan para pendatang yang merayakan momen lebaran di kampung halaman.
***

Hingga akhir tahun 1990-an, Acil Amas tak pernah kesulitan mendapatkan bahan baku pisang awak. Alam Binuang masih mampu menyedian pisang-pisang itu untuk Acil amas dan pembuat pisang rimpih lainnya di Binuang. Hingga menjelang awal tahun 2000-an Acil Amas mulai kesulitan mendapatkan bahan baku.
Banyak petani mengganti komoditi tanamannya dari pisang dan palawija menjadi komoditi perkebunan, berupa tanaman karet sebagian juga sawit. Hasil berkebun karet dinilai petani lebih menjanjikan dibanding bertahan dengan pisang dan palawija. Kondisi itu diperparah dengan serangan penyakit yang banyak mematikan pohon-pohon pisang milik petani kala itu.
Selain penyakit yang membuat banyak pohon pisang petani mati dan gagal berbuah, dan alih fungsi lahan pertanian menjadi kebun-kebun karet, mulai beroperasinya perusahaan-perusahan tambang batubara kian memperparah kondisi itu. Acil Amas pun kian kesulitan mendapatkan tandan-tandan pisang awak, bahan baku pisang rimpih olahannya.
“Dulu tak pernah kesulitan mendapat pisang awak dari para petani. Tapi sekarang bisa menyale sampai seribu pisang sudah bagus. Harganya pun mahal, Rp15.000,- sampai Rp20.000,- per seratus biji pisang.” kata Acil Amas.
Tanpa ingin menyalahkan siapa-siapa, petani yang mengganti pohon-pohon pisang dengan karet atau perusahaan-perusahan tambang yang telah menggali isi tanah dan merubah tanah-tanah pegunungan dan perkebunan menjadi lubang-lubang besar, Acil Amas mengaku tak akan berhenti menyale meski untuk mendapatkan bahan baku pisang sekarang tak lagi mudah.
Beruntung, Acil Amas sudah memiliki langganan yang membeli pisang rimpih olahannya. Pelanggannya adalah beberapa pedagang yang menjual lagi lagi pisang rimpih di Pasar Binuang. Ada juga pedagang dari Kandangan, HSS yang selalu memesan pisang rimpih olahanna dan dijual lagi sebagai oleh-oleh khas Binuang bersanding dengan dodol khas Kandangan.
Begitu pula dengan Untung. Meski perusahaan-perusahaan tambang telah banyak mengoyak lahan dan pegunungan di Binuang, ia tak beranggapan keberadaanya berdampak buruk wilayah terluas di Kabupaten Tapin itu. Menurutnya, keberadaannya juga berdampak positif. Dengan adanya perusahaan-perusaan tambang yang memang dikuasai tokoh-tokoh lokal Binuang itu, menurut Untung paling tidak menyediakan bidang pekerjaan baru, khususnya bagi warga asli Binuang.
“Untung ruginya mungkin fifty-fifty. Lagi pula perusahaan-perusahaan tambang itu juga memberi ganti rugi yang jauh lebih tinggi berkali-kali lipat dibanding harga jual tanah pada umumnya. Tak heran banyak warga Binuang yang kaya mendadak karena tanahnya dibeli perusahaan tambang,” kata Untung.
Sebagai warga pendatang, kata Untung, ia dan ratusan warga pendatang lainnya yang kini sudah beranak pinak dan menetap di Binuang lebih mengutamakan berdamai dengan lingkungan sekitar dengan tetap berprinsip di mana bumi dipijak di situ langit di junjung. “Meski keadaan kami para transAD yang sedikit banyak berperan pada perkembangan Kecamatan Binuang dapat dibilang miskin tidak kaya pun tidak,” kata Untung. (miris)